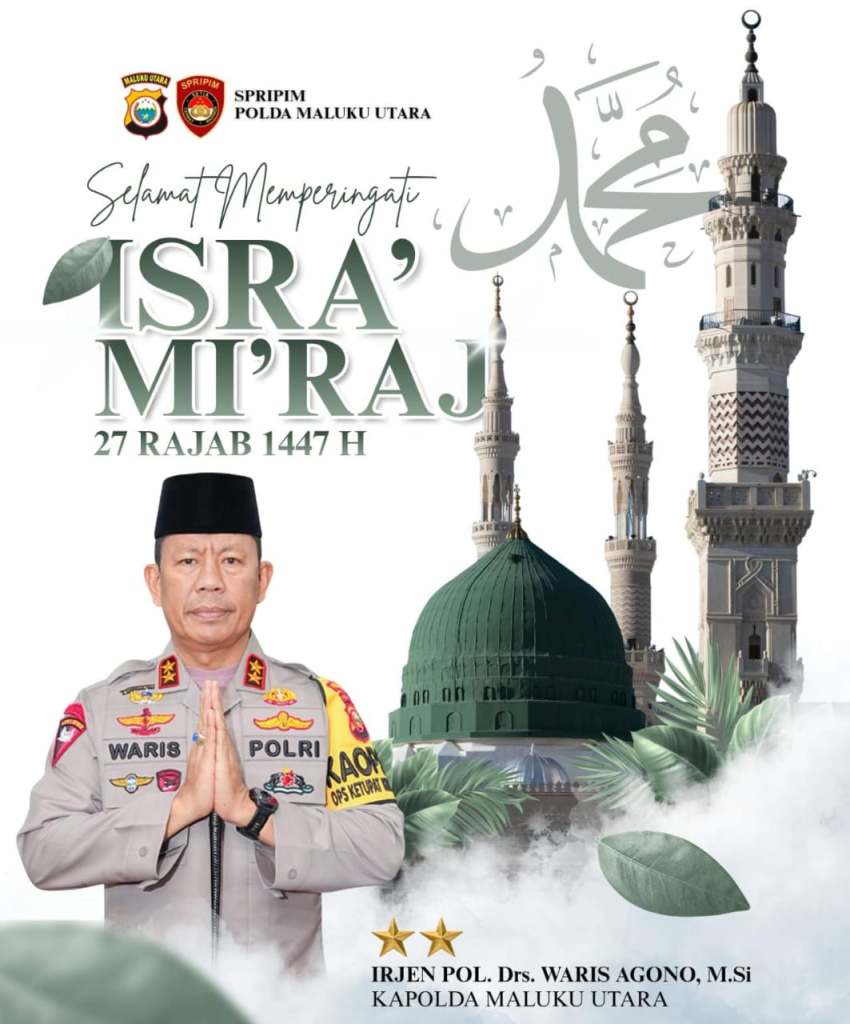Di tengah derasnya arus informasi, kematian prajurit TNI, anggota Polri, dan warga sipil akibat tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus menggores rasa nurani bangsa.
Setiap jasad yang dimakamkan adalah kegagalan negara untuk menjamin keselamatan warga dan aparat yang ditugaskan menjaga kedaulatan serta hukum. Sampai kapan masyarakat sipil dan aparat kita harus menjadi korban? Negara tidak boleh kalah.
Fakta lapangan menunjukkan pola kekerasan yang berulang: serangan terhadap pendulang, pembakaran fasilitas publik, serta serangan langsung ke pos-pos dan personel keamanan yang belakangan kembali menewaskan dan melukai prajurit serta warga.
Laporan-laporan terakhir memperlihatkan bahwa aksi-aksi itu tidak sekadar kriminalitas lokal, tetapi bagian dari konflik yang terorganisir dan terus beregenerasi.
Pertama: keselamatan warga sipil adalah harga mati. Negara berkewajiban melindungi setiap warganya tanpa syarat. Ketika warga sipil menjadi korban ditinggalkan, kehilangan tempat tinggal, atau menjadi target legitimasi tindakan negara untuk menegakkan hukum justru menguat, bukan melemah.
Rangkaian evakuasi, perlindungan, dan pemulihan harus betul-betul diprioritaskan; upaya keamanan tidak boleh sekadar reaktif, tetapi harus terintegrasi dengan jaminan kesejahteraan dan perlindungan jangka panjang.
Kedua: penghormatan terhadap hukum harus beriringan dengan ketegasan. Menumpas kelompok bersenjata bukan berarti mengerdilkan HAM; justru, penegakan hukum yang tegas dan transparan adalah bentuk penghormatan terhadap hak hidup masyarakat dan aparat yang bertugas.
Aparat TNI-Polri membutuhkan dukungan kebijakan, intelijen yang akurat, logistik memadai, serta koordinasi antar-instansi agar operasi mampu meminimalkan korban sipil sekaligus menumpas aktor kekerasan.
Pernyataan para pimpinan operasi bahwa penanganan ini kompleks dan memerlukan sinergi seluruh elemen negara harus dijadikan dasar tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
Ketiga: tindakan militer-polisi saja tidak cukup pembangunan dan politik kebijakan harus berjalan beriringan. Konflik di Papua dipenuhi akar masalah struktural: pembangunan yang timpang, ketimpangan ekonomi, marginalisasi budaya, dan ruang-ruang politik yang terbatas. Solusi yang hanya mengandalkan kekerasan akan menghasilkan siklus pembalasan.
Pemerintah harus mempercepat program-program pemberdayaan ekonomi, akses layanan publik, dialog yang tulus dengan pemangku kepentingan lokal, serta kebijakan yang menghadirkan keadilan sosial konkret bagi masyarakat Papua.
Keempat: siapa yang harus bertanggung jawab ketika aparat gugur? Negara. Setiap korban aparat adalah pengorbanan untuk menjaga kedaulatan dan hukum negara wajib membela keluarga korban, memperbaiki kelemahan operasional, dan mengevaluasi strategi agar peristiwa serupa tidak terulang.
Di saat yang sama, publik berhak menuntut transparansi: sejauh mana strategi yang dijalankan efektif, apa langkah pencegahan yang telah diambil, dan bagaimana upaya pencegahan radikalisasi dan perekrutan generasi muda ke dalam kelompok bersenjata diatasi.
Penutup: Negara harus memilih kalah secara moral atau berjuang menegakkan hukum dan melindungi warganya. Kemenangan di sini bukan semata menghabisi lawan, tetapi menghadirkan keadaan aman yang membuat anak-anak di Papua bisa sekolah tanpa takut, keluarga bisa mencari nafkah tanpa khawatir diserang, dan prajurit serta polisi bisa menjalankan tugas tanpa menjadi korban kelalaian atau ketidaksiapan institusi.
Jangan biarkan penderitaan warga dan gugurnya aparat menjadi statistik belaka. Jadikan setiap nyawa yang hilang sebagai momentum evaluasi kebijakan, penguatan kapasitas, dan komitmen nyata untuk menyudahi kekerasan.
Selamat jalan pada para pahlawan yang telah gugur — nama mereka mesti menjadi cambuk bagi negara untuk tidak lagi absen.
Negara harus hadir, bertindak efektif, dan memulihkan rasa aman. KKB tidak boleh menjadi takdir; kita bersama bisa mengakhiri siklus kekerasan ini dengan keberanian politik, kesungguhan pembangunan, dan ketegasan penegakan hukum. ***