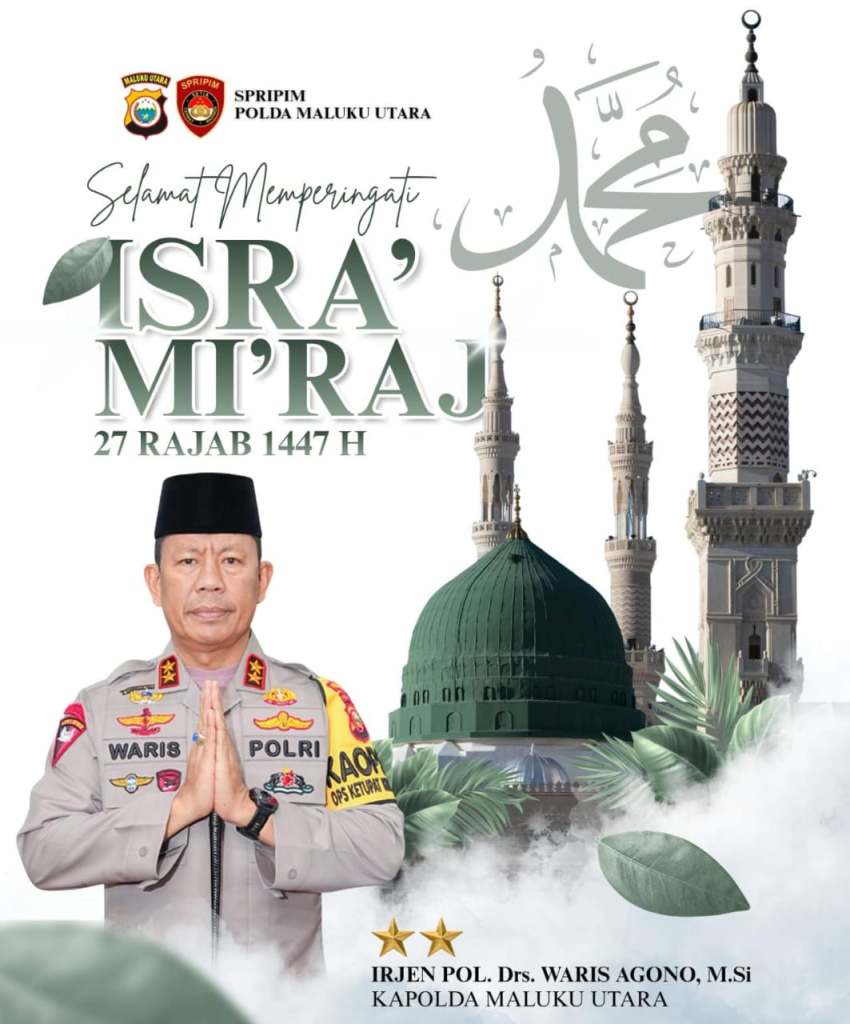Demokrasi, kritik adalah napas yang menjaga kekuasaan tetap berpijak pada realitas.
Ia adalah alarm ketika ada yang keliru, kompas saat arah pembangunan melenceng, dan jendela bagi pemerintah untuk melihat kenyataan di luar ruang rapat yang penuh angka dan laporan.
Namun sayangnya, dalam praktik politik kita, masih banyak pejabat yang alergi terhadap kritik. Kritik kerap dipandang sebagai cacian, dianggap penghinaan, bahkan dicurigai sebagai serangan terhadap legitimasi pemerintah.
Padahal, menganggap kritik sebagai cacian sama saja dengan mereduksi substansi demokrasi menjadi sekadar formalitas.
Demokrasi sejati bukan hanya tentang pemilu lima tahunan, melainkan juga tentang keterbukaan ruang bagi rakyat untuk mengawasi, mengingatkan, dan menyampaikan ketidakpuasan.
Tanpa kritik, pemerintah berisiko besar terjebak dalam euforia pencitraan, merasa kebijakannya selalu benar, dan akhirnya kehilangan koneksi dengan denyut kehidupan rakyat.
Perlu ditegaskan kembali, kritik tidak sama dengan cacian. Kritik lahir dari kepedulian, meski sering disampaikan dengan kata-kata yang tajam.
Kritik adalah bentuk cinta yang keras kepala; ia datang dari hati yang masih berharap ada perbaikan.
Sementara cacian lebih banyak lahir dari kebencian, tanpa tawaran solusi, tanpa niat membangun.
Ironisnya, di negeri ini sering kali perbedaan antara kritik dan cacian sengaja dihapuskan. Semua bentuk protes disapu rata dianggap cacian.
Padahal, kritik yang keras bisa justru menjadi modal penting untuk koreksi kebijakan.
Presiden ke-1 Republik Indonesia, Soekarno, pernah menegaskan: “Kritik yang membangun adalah tanda kecintaan kepada tanah air. Jangan takut dikritik, karena tanpa kritik kita tidak bisa memperbaiki diri.
Kalimat ini sederhana namun mendalam. Kritik bukan tanda kebencian, melainkan tanda bahwa rakyat masih peduli. Yang berbahaya justru ketika rakyat sudah berhenti mengkritik, karena itu berarti rakyat sudah kehilangan harapan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan dua sisi: pemerintah yang bekerja dan rakyat yang berani bersuara. Kritik adalah mekanisme alami untuk memastikan roda pemerintahan tidak keluar jalur.
Jika pemerintah menutup telinga, maka ia akan kehilangan kemampuan belajar dari rakyatnya.
Aristoteles, filsuf Yunani kuno, pernah berkata: “Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah hanya dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa.
Kritik hanya akan datang pada orang yang berbuat. Maka ketika pemerintah menerima kritik, sejatinya itu bukti bahwa pemerintah bekerja dan diperhatikan rakyat.
Namun, justru di sinilah kualitas kepemimpinan diuji: apakah kritik direspons dengan kedewasaan atau malah dengan kemarahan.
Nelson Mandela, tokoh besar dunia, punya pandangan bijak: “Saya tidak pernah kalah. Saya hanya menang atau belajar.”
Jika pemerintah mampu menanggapi kritik dengan sikap belajar, maka tidak ada yang dirugikan. Kritik yang benar bisa memperbaiki kebijakan.
Kritik yang salah pun bisa menjadi pelajaran tentang komunikasi publik. Pemerintah hanya akan rugi jika menutup pintu kritik, karena itu berarti menutup peluang untuk belajar.
Realitas hari ini menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah terlalu defensif menghadapi kritik. Alih-alih membuka ruang diskusi, kritik justru sering dijawab dengan tindakan hukum, pencitraan balik, atau bahkan framing negatif terhadap pengkritik.
Hal ini menciptakan suasana takut di masyarakat, membuat orang enggan bersuara, dan pada akhirnya melahirkan budaya diam yang berbahaya bagi demokrasi.
Padahal, media sosial, forum akademis, maupun diskusi publik adalah wadah sehat untuk mendengar aspirasi rakyat. Kritik yang muncul di ruang-ruang itu seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman.
Pemerintah perlu belajar membedakan antara kritik yang mengandung kepedulian dengan ujaran kebencian murni. Sayangnya, sering kali perbedaan ini kabur akibat kepentingan politik jangka pendek.
Seorang tokoh pers Indonesia, Mochtar Lubis, pernah mengingatkan: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut mendengar kebenaran, walaupun pahit.”
Kalimat ini menegaskan bahwa keberanian mendengar kritik adalah ukuran kedewasaan sebuah bangsa. Pemerintah yang dewasa adalah pemerintah yang tidak hanya siap dipuji, tetapi juga siap dikoreksi.
Jika pemerintah membuka diri terhadap kritik, maka kritik bisa berubah menjadi energi kolektif untuk membangun bangsa.
Kritik bisa menjadi umpan balik, sumber gagasan, bahkan inspirasi kebijakan. Dengan demikian, kritik tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra yang membantu pemerintah lebih dekat dengan rakyat.
Dalam sejarah, banyak kebijakan besar lahir dari kritik. Reformasi 1998 misalnya, lahir dari gelombang kritik rakyat terhadap pemerintahan otoriter.
Gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan juga berakar pada kritik panjang terhadap diskriminasi rasial. Kritik, jika dikelola dengan bijak, adalah motor perubahan.
Maka dari itu, sudah saatnya pemerintah kita membangun paradigma baru: berhenti menganggap kritik sebagai cacian. Sebaliknya, jadikan kritik sebagai alarm kewaspadaan, bahan introspeksi, dan ruang dialog.
Dengan cara ini, pemerintah akan lebih kuat, rakyat lebih percaya, dan demokrasi kita lebih sehat.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang sibuk membungkam, melainkan bangsa yang berani mendengar.
Kritik memang pahit, tapi bukankah obat yang manjur selalu pahit rasanya? Pemerintah harus menyadari bahwa menghargai kritik berarti menghargai rakyat, dan menghargai rakyat adalah inti dari demokrasi.
Kritik bukanlah cacian. Kritik adalah wujud cinta rakyat pada negerinya. Dan cinta sejati tidak pernah diam ketika melihat yang dicintainya berjalan salah arah. *